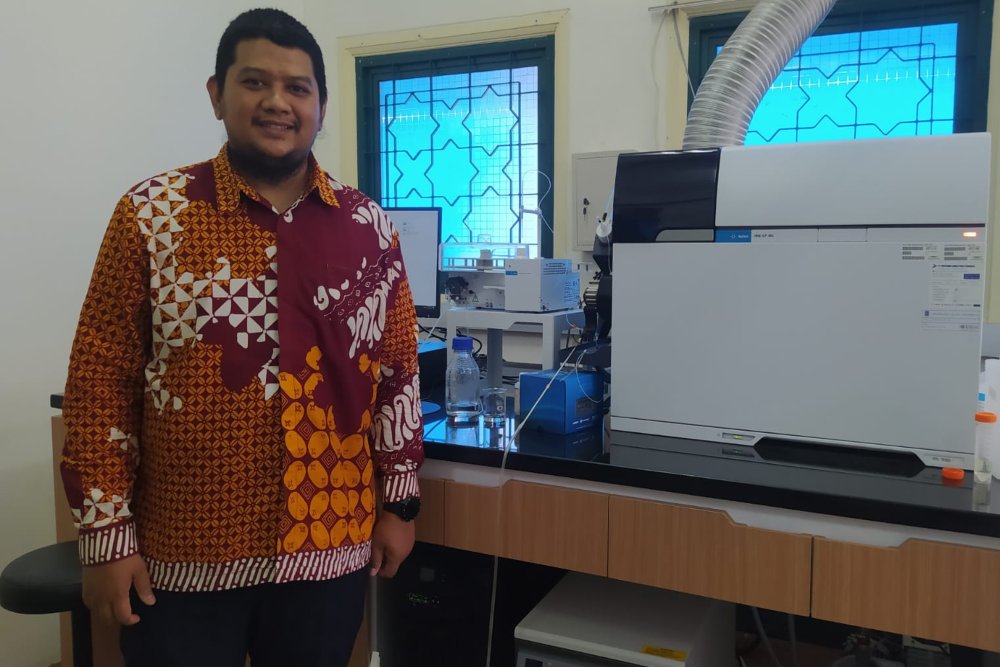Kertas Tii Mama Reti
“Surat Buat Mama Reti”
Mama Galo Zee
“Mama Saya Pergi Dulu”
Mama Molo Ja’o
“Mama Relakan Saya Pergi (Meninggal)”
Galo Mata Mae Rita Ee Mama
“Jangan Menangis Ya Mama”
Mama Jao Galo Mata
“Mama Saya Pergi”
Mae Woe Rita Ne’e Gae Ngao Ee
“Tidak Perlu Mama Menangis Dan Mencari Atau Merindukan Saya”
Molo Mama
“Selamat Tinggal Mama”
KENDARIPOS.CO.ID-Ya.. Surat terakhir anak SD dari Desa Ratogesa Nusa Tenggara Timur ini
menampar kita semua. Menambah catatan kelam potret Pendidikan kita saat ini. Surat
kecil yang ditulis dengan huruf tak seberapa rapi ini bukan sekadar pesan terakhir
seorang anak kepada ibunya.
Ini adalah komunikasi paling sunyi (Silenced
communication) dari seorang anak bangsa yang tak mampu lagi menemukan saluran
untuk bersuara di tengah hiruk-pikuk negeri yang seolah tuli pada jeritan mereka yang
terpinggirkan.
Tragedi ini bukan hanya tentang kisah kemiskinan atau ketidakadilan ekonomi. Ini
adalah tanda gagalnya sistem komunikasi sosial kita, antara negara dan warganya,
antara sekolah dan muridnya, bahkan antara masyarakat dan nuraninya sendiri.
Ia adalah jeritan yang tidak pernah benar-benar didengar, hanya menjadi gema di ruang
publik yang bising oleh perdebatan elite, Angka angka statistik, Pembangunan yang di
pamerkan, dan klaim-klaim keberhasilan yang berjarak jauh dari realitas desa.
Surat ini menjadi simbol betapa suara anak-anak miskin di daerah terpencil sering kali tenggelam dalam sistem yang lebih sibuk mengurus prosedur daripada memahami penderitaan.
Buku bukan lagi jendela dunia, melainkan tembok yang memisahkan mereka yang
mampu dan tidak mampu.
Surat itu akhirnya menjadi dokumen sosial yang menyakitkan: bukan hanya milik satu keluarga di Desa Ratogesa, melainkan milik kita semua sebagai bangsa. Ia menelanjangi kegagalan kita membangun sistem pendidikan yang benar-benar manusiawi pendidikan yang bukan sekadar mengajar membaca dan menulis, tetapi juga membaca penderitaan dan menulis kebijakan dengan empati.
Pemerintah gemar berbicara tentang “pendidikan gratis”, “wajib belajar”,
“Indonesia emas 2045”, tetapi komunikasi kebijakan itu berhenti pada level slogan.
Dalam teori komunikasi kebijakan, ini disebut top-down communication: negara rajin
mengirim pesan, tetapi malas menerima umpan balik dari realitas di bawah. Tidak ada
mekanisme serius untuk memastikan bahwa pesan “pendidikan untuk semua” benarbenar bermakna bagi anak di desa terpencil yang bahkan tidak mampu membeli buku
tulis.
Lebih ironis lagi, di tengah maraknya wacana kebijakan MBG (Makan Bergizi Gratis) yang menghabiskan anggaran ratusan triliun, kita justru dihadapkan pada fakta bahwa masih ada anak yang mati bukan karena tidak makan, tetapi karena tidak mampu membeli buku. Ini bukan soal menolak MBG, tetapi soal prioritas komunikasi kebijakan.
Bangsa seolah lebih sibuk membangun citra populis: memberi makan daripada
membangun ekosistem pendidikan yang adil, memberi alat untuk berpikir, membaca, dan
bermimpi.
Tragedi di NTT ini memperlihatkan apa yang disebut Jurgen Habermas sebagai
kegagalan ruang publik. Negara tidak lagi membangun dialog rasional dengan warganya,
melainkan sekadar memproduksi kebijakan dari pusat kekuasaan, lalu mengharapkan
masyarakat menyesuaikan diri. Tidak ada dialog, tidak ada empati struktural. Yang ada
hanyalah statistik: angka partisipasi sekolah, angka kemiskinan, angka gizi. Tetapi di balik angka itu, ada tubuh kecil yang menulis surat perpisahan karena merasa hidupnya sudah
tidak relevan bagi sistem.
Surat itu adalah bentuk komunikasi paling ekstrem: komunikasi terakhir. Dalam
ilmu komunikasi, ini bisa dibaca sebagai final message, pesan pamungkas ketika semua
saluran komunikasi sebelumnya gagal. Ia tidak menulis kepada menteri, tidak menulis
kepada presiden, tidak menulis kepada dinas pendidikan.
Ia hanya menulis kepada ibunya. Karena bagi anak itu, negara sudah terlalu jauh, terlalu abstrak, terlalu tidak hadir dalam kehidupannya yang konkret. Maka sesungguhnya, yang bunuh diri bukan hanya seorang anak. Yang ikut mati
adalah kepekaan sosial kita, empati kebijakan kita, dan fungsi komunikasi negara kita.
Kita sedang membangun negara yang rajin berbicara, tetapi miskin mendengar. Rajin
membuat program, tetapi malas membaca realitas. Rajin mengklaim keberhasilan, tetapi
gagap menghadapi kegagalan paling sunyi: seorang anak yang memilih mati karena tidak
mampu membeli buku.
Dan mungkin pertanyaan paling menyakitkan yang harus kita ajukan adalah: di
negeri yang menganggarkan triliunan untuk makan gratis, mengapa tidak ada satu buku
pun yang bisa menyelamatkan satu nyawa?
Pada akhirnya, tragedi ini seharusnya tidak berhenti sebagai kisah duka yang viral
lalu dilupakan. Ia mesti menjadi titik refleksi kolektif tentang bagaimana kita membangun
sistem komunikasi sosial yang lebih manusiawi.
Negara tidak cukup hanya berbicara
melalui kebijakan, tetapi harus mendengar melalui mekanisme empati yang nyata:
mendengar suara anak-anak miskin, guru di pelosok, dan orang tua yang hidup dalam
keterbatasan.
Surat dari Anak NTT ini mengingatkan kita bahwa dalam komunikasi, yang paling
berbahaya bukanlah konflik, melainkan keheningan (culture of silence) Karena
keheningan sering kali berarti tidak ada lagi yang merasa layak untuk berbicara.
Maka tugas kita sebagai masyarakat, pendidik, dan negara adalah memastikan tidak ada lagi
anak yang merasa harus menulis surat perpisahan hanya untuk didengar. Negara yang sehat bukan negara yang paling banyak bicara, tetapi negara yang paling mampu mendengar terutama mereka yang selama ini hidup dalam sunyi. (*)